Premanisme dan Tantangan Investasi Banten: Pengusaha Mesti Tumbuh Matang
Oleh Muhammad Sirod,
Pelaku Usaha
INVESTORTRUST.ID - Kasus pemerasan oleh sekelompok orang yang meminta “jatah proyek” hingga Rp 5 triliun di kawasan industri Cilegon, Banten, menjadi sorotan nasional. Aksi mereka terekam dan viral, dan kini aparat sudah menetapkan beberapa tersangka.
Sebagai pelaku usaha, saya menyambut langkah cepat aparat penegak hukum, khususnya kepolisian. Ini penting agar dunia usaha merasa dilindungi dan nyaman dalam berinvestasi, tanpa tekanan dari aktor-aktor yang bersandar pada kekuatan informal.
Langkah aparat ini adalah sinyal kuat bahwa di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, negara tidak akan mentoleransi premanisme. Dari awal Presiden Prabowo sudah tegas, tidak ada lagi kompromi terhadap pola ancaman dan kultur kekuasaan berbasis intimidasi. Bahkan, ormas-ormas besar yang selama ini dianggap kebal hukum pun tak luput dari proses penegakan hukum, bila terindikasi melakukan pelanggaran.
Baca Juga
Serap Rp 15 Triliun, Stok Beras Pemerintah di Bulog Rekor Tertinggi 57 Tahun
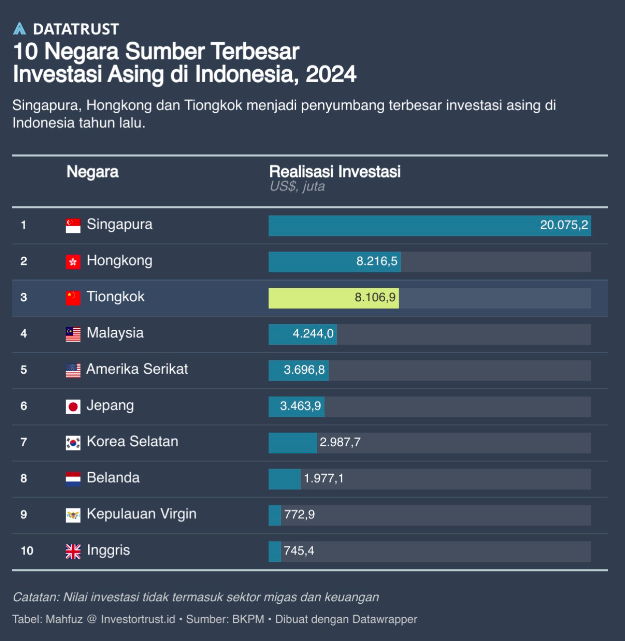
Jangan Sekadar Juru Izin
Cilegon adalah kawasan industri strategis. Di sana berdiri Chandra Asri—industri petrokimia hulu terbesar di Indonesia—yang menjadi fondasi bagi ribuan produk hilir dari plastik, energi, hingga tekstil.
Industri seperti ini padat modal, padat teknologi, dan padat karya. Tapi sangat sulit diakses oleh pelaku usaha kecil-menengah (UMKM) lokal, karena level teknologinya tinggi dan prosesnya rumit. Ini bukan sekadar soal jasa pengadaan, tapi soal masuknya ke dalam supply chain yang presisi dan global.
Tapi ketika pengusaha lokal merasa tidak dilibatkan di tengah kondisi perusahaan asing dilihatnya leluasa, muncul rasa timpang. Rasa ditinggalkan.
Dan ketika frustrasi bertemu kekuatan kolektif, muncullah pola “minta jatah”—yang oleh sebagian kalangan disebut premanisme. Saya tidak membenarkan caranya, tapi kita wajib melihat bahwa ada missing link: negara belum maksimal membina dan menyambungkan pengusaha lokal dengan dunia usaha besar.
Pengalaman serupa saya temui dulu waktu tinggal di Purwakarta. Di sana juga terjadi ketimpangan, tapi bentuknya beda: mayoritas pekerja pabrik diserap dari kalangan perempuan karena dianggap lebih cocok dengan pekerjaan repetitif dan terstandarisasi. Sementara laki-laki lokal, yang secara kultur diposisikan sebagai pencari nafkah utama, tersingkir.
Fenomena ini menimbulkan keresahan sosial. Bahkan, muncul dinamika baru di kos-kosan buruh, termasuk pola pergeseran identitas sosial (maraknya lesbian, gay, bisexual, dan transgender/LGBT). Ini bukan soal moralitas, tapi dampak dari industrialisasi yang tidak memperhatikan keseimbangan kultur dan kebutuhan sosial setempat.
Belajar dari pengalaman-pengalaman ini, kita perlu pendekatan lebih holistik. Negara harus hadir bukan hanya sebagai penegak hukum, tapi juga sebagai fasilitator, mediator, dan pembina kapasitas.
Tak bisa lagi negara bersikap netral pasif, apalagi sekadar jadi juru izinkan. Kalau tidak, ketimpangan akan terus meluas, dan dunia usaha akan tetap jadi objek tekanan—baik oleh premanisme, maupun oleh frustrasi sosial yang tak tersalurkan.
Pembanding: Kawasan Industri Batang
Sekarang bandingkan dengan kawasan industri Batang di Jawa Tengah. Kenapa di sana dunia usaha tumbuh dengan minim gesekan?
Hal itu karena dua faktor utama: pertama, upah minimum regional (UMR) di Jateng jauh lebih rendah dibandingkan kawasan industri di Jabodetabek atau Jawa Barat. Kedua, infrastruktur jalan tol yang dibangun di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membuka akses dari Jakarta ke Batang dalam waktu tempuh hanya 4–6 jam.
Dua hal ini membuat banyak perusahaan—terutama dari Bekasi, Karawang, bahkan Tangerang—pindah ke Batang. Ongkos produksi lebih murah, logistik efisien, dan pemerintah pusat maupun daerah aktif memfasilitasi.
Lahan di Batang sudah disiapkan, perizinan disederhanakan, dan yang penting: tidak ada tekanan dari kelompok informal ataupun kelompok preman lokal. Kenapa? Karena ekosistemnya masih baru, problem sosial belum terlalu kompleks, dan strategi pembangunannya sudah belajar dari kegagalan kawasan industri sebelumnya.

Baca Juga
Jadi, kita tidak bisa terus membiarkan investasi besar jadi objek ancaman oleh siapa pun. Jika ini dibiarkan, maka Indonesia hanya akan dilihat sebagai pasar, bukan tempat produksi.
Investor asing bisa berpaling ke negara jiran yang “ease doing business”-nya lebih baik, seperti Vietnam dan Malaysia yang juga lebih menjamin stabilitas dan efisiensi. Kita akan kalah bukan karena kalah sumber daya, tapi karena kalah dalam menata sistem dan kultur probisnis.
Saya percaya, Presiden Prabowo punya kemauan politik yang kuat. Beliau paham bahwa untuk menjadikan Indonesia negara kuat, kita harus punya sistem ekonomi yang berdaulat dan profesional.
Aparat harus tegas. Pengusaha lokal harus tumbuh matang. Pemerintah harus aktif menjembatani, bukan hanya mengatur. Dan, dunia usaha besar harus sadar akan tanggung jawab sosialnya, bukan hanya mengejar efisiensi semata.
Sebagai bangsa, kita perlu mengakhiri era “jatah-jatahan”, dan membuka babak baru: profesionalisme. Dunia usaha bukan tempat kompromi dengan kuasa informal, tapi arena pertumbuhan, inovasi, dan keberpihakan pada keadilan. Investasi bukan untuk dikeruk guna kantong pribadi atau kelompok, tapi untuk dikelola bersama menjadi bangsa sejahtera.
Kita tidak butuh drama baru. Yang kita butuh orkestrasi baru yang harmonis—antara negara, pelaku usaha, dan rakyatnya. (ad)

